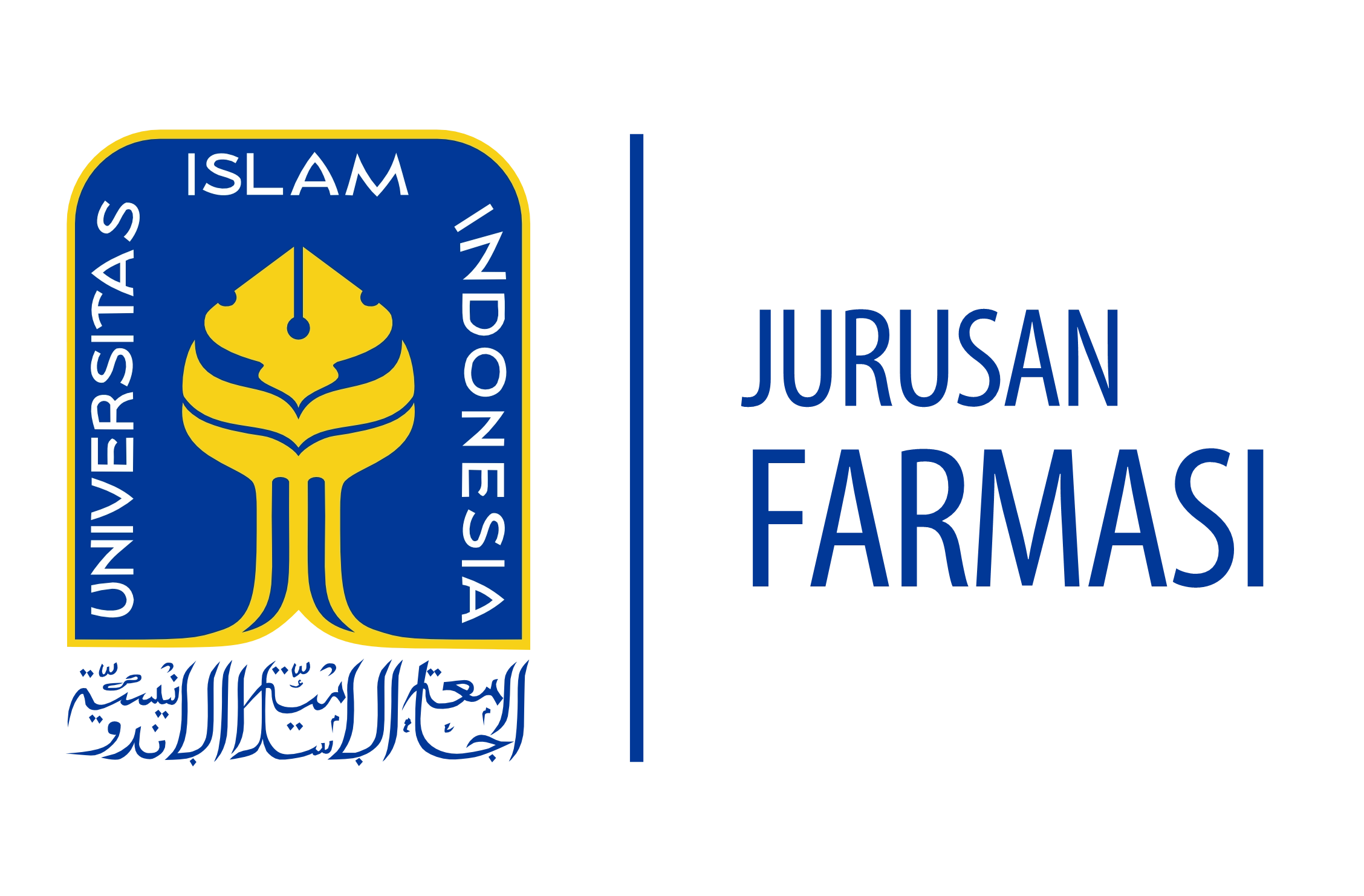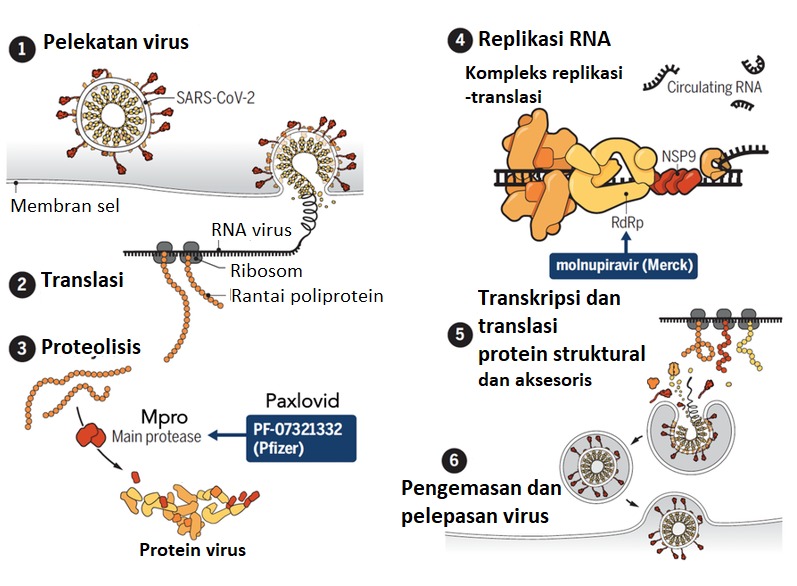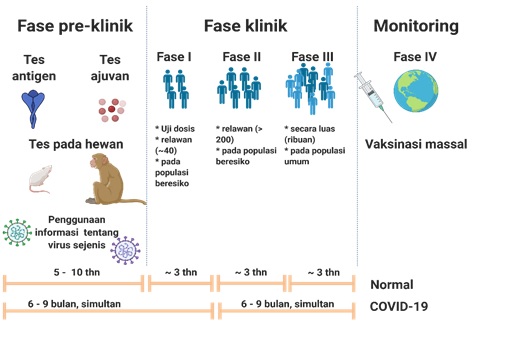Isu pelestarian lingkungan makin marak dan mendapat perhatian saat ini, namun demikian kerusakan alam tetap saja terjadi. Sumber kerusakannya bermacam-macam dan sebagian besar permasalahan tersebut disebabkan adanya kontribusi dari manusia baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kerusakan lingkungan yang tidak mendapat penanganan yang serius, lambat atau cepat dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Dampak tersebut dapat menyebabkan kecatatan dan bahkan kematian serta kerugian materiil.
Dalam Islam, menjaga kesinambungan alam bukanlah hal yang baru. Al-Qur’an telah mengangkat mengenai isu lingkungan sejak berabad-abad yang lalu, dalam Al A’raf ayat 56 yang artinya:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”
Hal tersebut juga disinggung dalam surat Al Baqarah ayat 60 yang artinya:
““Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 60)
Berkaitan dengan pengelolaan bumi dan isinya, Islam mengajarkan dan memposisikan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu makhluk yang ditugaskan menjadi pemimpin di bumi termasuk didalamnya untuk menjaga kelestarian alam dengan sebaik-baiknya. Tugas tersebut seperti disebutkan dalam AL Quran sebagaimana dituliskan dalam AL Baqarah ayat 30 yang artinya
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
Bidang kesehatan khususnya obat-obatan, saat ini telah berkembang pesat dibandingkan periode pengobatan berabad-abad yang lalu. Peradaban sebelumnya seperti di China, Sumeria dan Persia, Arab atau nenek moyang kita di Indonesia, masih menggunakan obat yang berasal dari alam dan diolah dengan sederhana. Obat-obatan diambil dari alam seperti tumbuhan, bagian tubuh hewan yang dikeringkan, dan tanah. Bahkan, pengobatan yang lebih kuno, melibatkan kepercayaan bahwa sakit disebabkan oleh makhluk halus atau tahayul. Sedangkan saat ini, obat yang dipergunakan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit makin beragam jenisnya, sudah lebih kompleks pembuatannya dan banyak yang menggunakan bahan sintetis.
Obat-obatan tersebut memiliki berbagai macam fungsi atau khasiat, seperti untuk mengobati nyeri, radang, infeksi, dan kanker; pencegahan penyakit seperti aspirin untuk pencegahan stroke dan memelihara kondisi tubuh seperti penggunaan multivitamin. Terkadang, obat-obatan yang dipergunakan pasien, tidak selalu habis dikonsumsi saat penyakitnya sembuh atau kondisi pasien terkontrol dengan baik. Dalam keadaan tersebut, obat-obatan kemudian disimpan di rumah. obat-obat tersebut telalu lama disimpan melebih batas waktunya, dan akhirnya kadaluarsa atau ada yang rusak saat disimpan. Jika sudah ED atau rusak, kebanyakan masyarakat membuang obat-obatan tersebut langsung ke tempat sampah.
Dengan kemajuan teknologi, banyak ditemukan obat dengan kandungan zat aktif baru dengan efek yang lebih kuat dari obat tradisional. Selain itu, obat-obatan modern lebih bisa bertahan lama, sehingga memungkinkan obat dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan tidak mudah rusak pada kondisi tertentu. Sehingga, dengan karateristik obat-obatan modern yang mampu bertahan lama, maka limbah obat modern yang tidak ditangani dengan baik akan terakumulasi dan mencemari lingkungan.
Meski jumlah limbah obat dari limbah rumah tangga di Indonesia belum ada data yang komprehensif melaporkannya, namun dugaan jumlahnya yang cukup besar residu zat aktif obat yang tertinggal di lingkungan tetap patut diwaspadai. Hasil temuan BRIN (Badan Riset Indonesia) menunjukkan adanya residu obat penurun panas dan nyeri parasetamol dan antibiotik amoksisilin di Sungai Ciliwung. Hasil tersebut menegaskan bahwa praktek pembuangan obat masih belum seperti yang diharapkan. Jumlah cemaran bahan aktif obat tersebut yang relative sedikit kemungkinan belum dapat mempengaruhi lingkungan dan manusia secara signifikan pada saat ini, Namun demikian, tanpa penangganan yang baik, cemaran tersebut dapat meningkat jumlahnya. Cemaran bahan aktif antibiotika di lingkungan, dapat mematikan bakteri baik yang berguna untuk melakukan penguraian. Selain itu, efek negatif dari cemaran antibiotik adalah terjadinya mutasi bakteri yang dapat memicu resistensi terhadap antibiotik. Resistensi bakteri dapat berakibat peningkatan biaya perawatan, mempersempit pilihan obat yang dapat diberikan kepada pasien dan juga meningkatkan resiko kematian.
Dengan karakter obat yang beragam, dapat dikatakan bahwa pencemaran dapat memunculkan dampak yang berbeda-beda. Hasil kajian penelitian dari negara lain yang dilakukan menunjukkan bahwa bioakumulasi kombinasi zat aktif yang bersifat estrogenik di jaringan ikan, kemungkinan besar mendorong terjadinya feminisasi pada ikan liar yang hidup di sungai-sungai di Inggris. Selain itu, penurunan populasi burung nasar yang merugikan di Pakistan sebagian dikaitkan dengan kerentanan burung nasar terhadap konsumsi ternak yang diobati dengan diklofenak. Secara khusus, diklofenak ditemukan di ginjal seluruh 25 burung nasar yang mati akibat gagal ginjal, dengan konsentrasi berkisar antara 0,051–0,643 μg/g.
Selain temuan dari negara-negara tersebut, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Ibuprofen yang banyak digunakan karena sifat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretiknya, dapat bertindak sebagai agen antimikroba terhadap Staphylococcus aureus pada pH di bawah 7. Hal ini berarti bahwa dalam lingkungan asam, seperti yang terdapat pada bagian tubuh tertentu atau dalam kondisi laboratorium, ibuprofen mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif tersebut. Pada ikan zebra (Danio rerio), proses penetasan telur dilaporkan mengalami keterlambatan akibat paparan obat antiinflamasi nonsteroid. Paparan diklofenak pada ikan zebra juga dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan insang.
Berdasarkan temuan tersebut, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan tata cara penangangan obat ED atau rusak yang tidak lagi dipakai. Selain itu, obat-obat yang dibuang dalam kemasan utuh beresiko dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan ataupun dipakai untuk kondisi yang tidak sesuai dengan penyakitnya dan dapat berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Pencegahan pencemaran lingkungan yang dapat membawa dampak tidak baik, pernah disampaikan oleh Rasulullah: “Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang diam yaitu air yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya.” (HR Bukhari). Makna dari hadist tersebut dapat ditujukan untuk kehati-hatian dalam menjaga lingkungan
Dalam upaya untuk mengurangi limbah dan cemaran obat, beberapa hal dapat dilakukan seperti dijabarkan sebagai berikut.
- Lakukan pencegahan penumpukan obat kadaluarsa atau rusak di rumah.
Langkah awal adalah mengidentifikasi dulu obat yang diperlukan, bisa dilihat dari pola penyakit yang sedang berkembang atau penggunaan obat yang pernah digunakan sebelumnya. Hindari pembelian obat dalam jumlah yang berlebih, sesuaikan saja dengan kebutuhan atau lebihkan secukupnya untuk cadangan obat yang bersifat darurat. Perhatikan obat yang memiliki waktu kadaluarsa pendek. Cek berkala obat yang disimpan di rumah, dan pilih obat yang akan atau sudah kadaluarsa. Obat yang akan kadaluarsa, dapat dipergunakan terlebih dulu. Selanjutnya, simpan obat di tempat dan cara yang benar. Jauhkan dari tempat yang lembab, terkena panas atau sinar matahari. Teknis penyimpnan bisa juga mengikuti aturan penyimpanan dari leaflet atau menanyakan ke apotek terdekat.
- Untuk obat yang sudah kadaluarsa atau rusak, pastikan jangan dibuang langsung ke tempat sampah ataupun saluran air.
- Jika dimungkinkan, bawalah limbah obat ke fasilitas kesehatan atau apotek yang menerima obat-obatan yang kadaluarsa atau ke program pengumpulan obat yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan ini tidak selalu ada, dan silahkan ditanyakan ke apotek atau layanan kesehatan tentang hal tersebut kapan pelaksanaannya.
Apabila pembuangan dilakukan secara mandiri, pembuangan yang baik dilakukan dengan penanganan obat terlebih dulu. Secara umum, langkah pertama adalah mengeluarkan obat dari kemasan/wadah aslinya. Campurkan obat dengan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti tanah, serbuk/ampas serbuk kopi atau kotoran dalam wadah tertutup. Untuk obat sirup, buanglah cairan setelah diencerkan. Potonglah tube salep/krim terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah. Buang kemasan obat (dus/blister/strip/bungkus lain) setelah dirobek atau digunting. Untuk sediaan insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Selain itu, kemasan obat juga harus dirusak sebelum dibuang, agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Etiket berisi data pribadi dilepas.
Akan lebih baik lagi jika penanganan obat disesuaikan dengan bentuk atau jenis obat dengan tahapannya dapat dilakukan seperti berikut:
- Obat Padat
Tablet, kaplet, kapsul, dan supositoria dikeluarkan dari kemasan aslinya, dihancurkan hingga tidak utuh, lalu dicampur dengan bahan tidak layak konsumsi (misalnya tanah atau ampas kopi). Campuran dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dibuang ke tempat sampah rumah tangga.
2. Obat Cair
Sirup atau cairan obat luar yang mengental atau berendap diencerkan dengan air dan dikocok. Setelah itu, obat dibuang melalui saluran pembuangan air (jamban). Hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Untuk menghindari keberbahayaan, botol yang telah dihancurkan dapat dibungkus lagi dengan wadah yang seperti kaleng atau botol air mineral yang sudah tidak terpakai.
3. Obat Semi Padat
Krim, salep, dan gel dikeluarkan dari tube dengan cara menggunting kemasan. Isi dapat diencerkan dengan air lalu dibuang ke jamban, sedangkan kemasan dibuang terpisah ke tempat sampah.
4. Inhaler atau Aerosol
Isi inhaler atau aerosol dikosongkan dengan menyemprotkan perlahan ke dalam air. Pastikan kemasan sudah kosong dan jangan dilubangi, ditekan, atau dibakar.
5. Obat Sitotoksik/Antikanker
Obat sitotoksik dipisahkan dari obat lain dan dikembalikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Obat ini tidak boleh dibuang ke jamban atau tanah. Obat ini sangat berbahaya jika terkena bagian tubuh yang sehat, sehingga tidak disarankan untuk disimpan apabila sudah tidak dipakai lagi.
6. Antibiotik, Antivirus, dan Antijamur
Obat dibiarkan dalam kemasan asli, dicampur air, didiamkan beberapa minggu, lalu dikubur untuk mencegah resistensi.
Dengan melakukan tahapan penanganan obat rusak atau kadaluarsa tersebut, tiap individu dan rumah tangga berperan dalam penurunan cemaran bahan aktif obat. Memang tidak mudah membiasakan penanganan obat sebelum dibuang, namun manfaatnya sangat besar bagi terutama bagi generasi selanjutnya. Kestarian alam yang dijaga dengan sungguh-sungguh merupakan warisan terbaik untuk anak cucu kita di masa mendatang.
Hingga saat ini, belum banyak masyarakat mengetahui penanganan obat sebelum dibuang. Pengetahuan tersebut yang mungkin awalnya bukan hal yang penting, tidak mustahil akan menjadi isu yang makin penting untuk mendapat perhatian di masa mendatang.
Penulis: Apt. Okti Ratna Mafruhah, M.Sc., Ph.D.
Referensi
Gibson, R.; Smith, M.D.; Spary, C.J. Mixtures of Estrogenic Contaminants in Bile of Fish Exposed to Wastewater Treatment Works Effluents. Environ. Sci. Technol. 2005, 39, 2461–2471.
Halling-Sørensen B, Nors Nielsen S, Lanzky PF, Ingerslev F, Holten Lützhøft HC, Jørgensen SE. Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environment- a review. Chemosphere. 1998;36:357–93.
Mauro M, Lazzara V, Arizza V, Luparello C, Ferrantelli V, Cammilleri G, et al. Human Drug Pollution in the Aquatic System: The Biochemical Responses of Danio rerio Adults. Biology (Basel). 2021;10:1064.
Oaks, J.L.; Gilbert, M.; Virani, M.Z.; Watson, R.T.; Meteyer, C.U.; Rideout, B.A.; Shivaprasad, H.L.; Ahmed, S.; Chaudhry, M.J.I.; Arshad, M.; et al. Diclofenac residues as the cause of vulture population decline in Pakistan. Nature 2004, 427, 630.
https://www.kompas.id/artikel/sungai-sungai-di-dunia-tercemar-obat-obatan-citarum-ikut-diteliti
https://rsa.ugm.ac.id/yuk-kenali-pembuangan-obat-rusak-dan-kedaluwarsa-yang-baik-dan-benar/